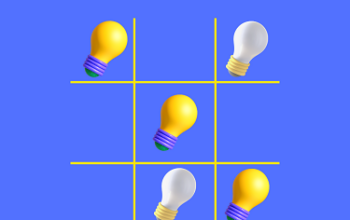Belum purna bulan Agustus, bulan kemerdekaan negeri kita tercinta, media sudah geger dengan rentetan berita seru lainnya. Kabar pertama tentang peresmian gedung ANNAS di Bandung dan yang kedua adalah statement Wakil Gubernur Jabar tentang poligami dan nikah muda sebagai solusi mencegah HIV.
Menurut saya berita yang kedua akan menarik untuk dibahas lebih dulu. Apalagi kalau kita ingat, beliau juga pernah mengeluarkan statement yang cukup hadeuh terkait meninggalnya seorang siswa setelah di-bully dan dipaksa menyetubuhi kucing.
Statement tentang nikah muda dan poligami mungkin terdengar biasa, kalau diucapkan di forum kajian agama. Tapi masalahnya, Pak Wagub bicara bahwa dua hal ini adalah solusi – alih-alih masalah baru – dari penyebaran HIV.
Lucunya lagi, tidak jauh setelah Pak Uu menyampaikan pendapatnya, Pak RK melalui akun instagramnya menyatakan ketidaksetujuannya tentang pandangan tersebut. Hm, rupanya ada pasangan yang mulai tidak sejalan sehingga salah satunya ingin memilih poligami. Hehe.
***
Sebagai manusia yang sangat lemah, Saya termasuk orang yang malas membahas poligami. Apalagi kalau hal tersebut disejajarkan dengan cara meneladani nabi. Memangnya saya ini manusia sehebat apa sampai-sampai ingin dibilang sudah bisa meniru nabi.
Sedangkal pengetahuan yang saya punya, baginda Nabi Muhammad saw melakukan poligami karena menyelamatkan anak yatim dan janda-janda syuhada. Artinya, menurut saya lagi, sama sekali tidak ada dorongan nafsu sebagai landasannya.
Selain itu, yang dinikahi umumnya janda tua. Bukan gadis belia yang kinyis-kinyis karena istri pertamanya sudah kisut. Dari sini saja sudah jelas ada perbedaan paham antara poligami di zaman nabi dengan yang dilakukan banyak orang saat ini.
Poligami pada zaman nabi, yang pertama adalah jalan mulia untuk menolong kehidupan perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan. Kedua, poligami di masa itu justru bukan izin untuk menikah dengan banyak perempuan, melainkan sebagai batasan untuk tidak memiliki terlalu banyak istri seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah.
Klausa “empat orang” pun tidak berhenti di batas kuantitas, melainkan disambung dengan aspek kualitas yaitu “memberikan keadilan”. Tetap ada pemenuhan hak dan tanggung jawab pria dan wanita. Pendek kata, poligami bisa saja dikatakan sebagai obat, jika penyakitnya tepat yaitu menghidupi janda-janda tua.
Tapi dalam hal ini, Pak Wagub barangkali hendak menggarisbawahi poligami dan nikah mudah sebagai langkah tepat mencegah zina ketimbang bapak-bapak “jajan” dan anak muda bergaul bebas. Tapi tetap saja ini nggak ada hubungannya dengan pencegahan HIV karena bapak-bapak di sini sedang mencari “obat” untuk nafsunya. Bukan untuk HIV.
HIV sebagai penyakit jasmani – mungkin benar – salah satu cara penularannya adalah dari hubungan intim. Tapi bukankah ada juga orang yang tidak sadar sebagai pembawa virus, lalu menikah resmi dan menularkannya pada istri dan anaknya?
Lalu, di sebelah mananya poligami yang demikian bisa ditempatkan sebagai cara mencegah HIV?
Kalaupun menikah cepat – diksi yang saya pilih ketimbang menikah muda – adalah solusi bagi syahwat anak muda, lalu apa kabar bapak-bapak tua dan beristri yang juga masih lirik kanan-kiri-depan-belakang seolah belum punya pasangan?
Andaikata zina disebut sebagai salah satu penyebab HIV, maka Pak Wagub yang notebene dikenal berasal dari lingkungan pesantren, seharusnya tampil sebagai seorang pendidik, memberikan pelajaran dan pemahaman tentang bagaimana membentengi diri dari pergaulan bebas.
Tidak harus buru-buru menikah karena toh nabi juga meneladankan puasa sebagai salah satu cara menahan nafsu, termasuk syahwat. Alih-alih menjadi solusi, menikah cepat-cepat justru bisa menjadi masalah baru. Apalagi jika pasangan ternyata tidak siap secara fisik, mental dan finansial.
Menikah dan poligami bukan satu-satunya pelajaran di dalam Islam yang menjadi solusi mencegah perzinaan. Ada pelajaran tentang pardah yaitu menundukkan pandangan bagi laki-laki dan menutup aurat bagi perempuan. Islam juga mengajarkan puasa bagi yang masih membujang.
Bahkan, kewajiban untuk menuntut ilmu pun bisa menjadi cara untuk mengendalikan diri. Karena dengan ilmu, kita akan tahu banyak hal, terasah daya pikir kritis sehingga tidak terburu-buru mengambil keputusan. Apalagi berkomentar.
Mengurai Benang Kusut Informasi
Masalah menikah muda dan poligami selanjutnya akan saya kaitkan dengan peresmian Gedung ANNAS di Bandung. Terdapat bahan diskusi yang sama pada keduanya yaitu informasi yang kurang mendalam dipahami, ditelan mentah-mentah, namun terburu-buru mengambil langkah.
Poligami sebagai cara baginda nabi menyelamatkan janda syuhada, secara spontan dianggap sebagai teladan yang harus dilaksanakan. Menikah muda pun dianggap sebagai Ibadah wajib, bahkan mengalahkan kewajiban mempelajari ilmu berumah tangga sebelum menikah.
Sementara itu, peresmian gedung dakwah ANNAS yang notabene merupakan wadah Aliansi Anti Syiah, pastilah juga karena ada informasi yang kusut tentang keyakinan tersebut. Di luar masalah sepakat atau tidak, bukankah para penganut Syiah juga berhak untuk menentukan pilihan keyakinannya?
Memasuki bulan September, ketiga poin peristiwa di atas tampak tidak sejalan dengan sebuah perayaan Hari Perdamaian Internasional di tanggal 21 nanti. Perdamaian tidak selalu identik dengan perang. Namun hidup tenang berdampingan dengan yang berbeda juga definisi dari “damai”.
Alih-alih menggali makna damai, saya ingin memberikan sudut pandang yang berbeda. Ternyata, media bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi media bisa membawa informasi yang mendamaikan. Tapi di saat yang sama, kekeliruan menganalisa, menyajikan dan menyebarkan berita juga menjadi pemicu perilaku buruk seseorang terhadap orang yang lain.
Tom Nichols dalam bukunya “The Death of Expertise” (2017) mengemukakan fakta menarik tentang matinya kepakaran. Nichols memaparkan bahwa media telah mengambil alih keilmuan, sejak semakin banyak orang lebih percaya kepada pemberitaan media tanpa perlu melihat siapa yang bicara.
Artinya, tak sedikit orang yang bertindak hanya dengan berbekal informasi yang disebarkan media. Sebaliknya, mulai jarang orang yang menggali informasi langsung dari sumber yang valid dan akurat. Dalam hal ini, saudara-saudara kita yang meyakini Syiah sebagai keyakinannya sedang diguncang badai akibat “matinya kepakaran” tersebut.
Akumulasi dari kesimpangsiuran informasi tentang Syiah, poligami dan menikah inilah yang seharusnya disikapi bersama. Perlu keterampilan berpikir kritis terhadap setiap pemberitaan media, sehingga kita bukan hanya menjadi followers pasif yang asal share berita, tanpa memilah dan menggali kebenaran informasi yang disajikan.
Bayangkan, hanya karena sebaris informasi, dunia toleransi bisa ruwet lagi.
Kita Bisa Apa?
Dari simpang siur informasi yang tersebar, pembaca berita bukanlah sekelompok orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita tengok akar dari semua kekacauan ini, yaitu masih banyak orang yang belum menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.
Jika seseorang sudah mencapai titik damai, sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka tentu ia akan puas dengan apa yang dia punya. Alih-alih meminta orang lain untuk ikut melakukan apa yang dia lakukan, ia cukup berjalan on track tanpa perlu memaksa siapapun yang berbeda jalur.
Damai sebagai lawan dari kondisi chaos harus diperluas maknanya, sehingga tidak hanya terbatas pada perang bersenjata saja. Kedamaian di dalam diri seseorang tidak lain adalah sebuah ketenangan berpikir dan berperilaku, ketika ia sudah bisa meredam ego dan mengendalikan daya pikirnya.
Berpikir tenang dan berperilaku menenangkan, adalah wujud konkret dari menciptakan kondisi damai. Bukan berarti tidak berhak mengkritisi atau mengingatkan, namun jangan sampai menghancurkan hanya karena perbedaan.
Sebaliknya, mereka yang merasa dibedakan juga tidak perlu terus-terusan playing victim, seolah-olah minoritas adalah kelompok yang paling wajib dibela. Lebih baik, bela diri sendiri dengan menunjukkan kerja nyata, kita bisa apa untuk Indonesia, kalian bisa apa untuk dunia.
Terima kasih.
(Redaksi Love for All)